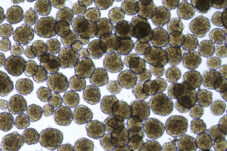KABARIKA.ID, MAKASSAR – Kemajuan suatu negara tidak selalu mencerminkan tingginya kebebasan pers. Jepang sebagai contohnya. Dalam laporan tahunan Indeks Kebebasan Pers Dunia 2023 yang dikeluarkan oleh organisasi nirlaba Reporters Without Borders, Jepang berada di urutan ke-68 dari 180 negara dan wilayah yang disurvei.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Melansir laman Deutsche Welle, tradisi, kepentingan ekonomi, tekanan politik, dan ketidaksetaraan gender membebani kerja para wartawan di negara sakura itu.
Jepang mungkin unggul di bidang manga dan teknologi. Namun di bidang kebebasan pers, peringkat negara ini tergolong rendah.

Ini berarti, negara dengan peringkat ekonomi terbesar ketiga di dunia ini berada di bagian bawah negara-negara G7 dalam hal kebebasan pers, dan berada di antara Lesotho dan Panama.
“Jepang, negara demokrasi parlementer, menjunjung tinggi prinsip media dan pluralisme. Namun, beratnya tradisi, kepentingan ekonomi, tekanan politik, dan ketidaksetaraan gender menghalangi jurnalis untuk sepenuhnya menjalankan peran mereka dalam menuntut transparansi dari pemerintah,” kata studi yang diterbitkan pada 3 Mei itu.

Norwegia menduduki puncak indeks kebebasan pers selama tujuh tahun berturut-turut versi Reporters Without Borders yang berbasis di Paris itu.
Kemudian Irlandia berada di tempat kedua. Jerman berada di posisi ke-21, turun dari posisi ke-16 pada studi sebelumnya.
Korea Utara menduduki peringkat terakhir dari 180 negara. Sementara Cina di posisi 179, turun empat peringkat dari laporan 2022, dan Vietnam berada di peringkat ke-178. Indonesia sendiri berada pada peringkat ke-108.
Pengaruh Klub Pers yang Didukung Pemerintah
Salah satu penyebab rendahnya tingkat kebebasan pers di Jepang adalah adanya sistem klub pers yang disetujui pemerintah bagi tiap-tiap kementeriannya.
Selain itu, menurut akademisi dan jurnalis, ada pula kecenderungan media untuk melakukan sensor sendiri saat ada tekanan sekecil apa pun dari pemerintah atau mitra bisnis yang berpengaruh.
Itulah yang membuat Jepang sangat tertinggal di belakang negara-negara seperti Liberia, Bosnia-Herzegovina, dan Burkina Faso dalam hal kebebasan pers.
“Kebebasan berbicara dijamin di Jepang berdasarkan Pasal 21 Konstitusi, tetapi ada masalah, seperti sistem klub pers. Itulah sebabnya Jepang mendapat peringkat sangat rendah dalam indeks kebebasan pers,” kata Renge Jibu, profesor di Tokyo Institute of Technology dan anggota dari Japan Association of Media, Journalism and Communication Studies.
Keberadaan Klub Wartawan atau yang disebut “Kisha kurabu”, dapat ditelusuri kembali hingga ke tahun 1890 dan larangan akses wartawan yang diberlakukan oleh kekaisaran saat itu.
Sebagai tanggapannya, para jurnalis bersatu dengan dukungan perusahaan surat kabar, dan membentuk klub pers pertama dan melobi untuk mendapatkan akses.
Klub-klub ini umumnya hanya terdiri dari jurnalis yang bekerja di outlet media besar Jepang. Para anggotanya memiliki akses eksklusif ke sumber-sumber resmi, dan untuk mempertahankan akses tersebut mereka harus mematuhi garis haluan dari pemerintah.
Terlepas dari tekanan dari media asing saat ini, sistem klub kisha tetap efektif sejak saat itu. “Sistem ini memberikan kekuatan kepada politisi dan birokrat untuk menakut-nakuti jurnalis dan perusahaan media, jika mereka melaporkan berita negatif atau tidak menyenangkan,” papar profesor Renge Jibu.
Menurutnya, kementerian akan mengatakan mereka ada keterbatasan ruang untuk wartawan dan ada kebutuhan untuk melakukan pemeriksaan latar belakang, tetapi di sisi lain klub kisha sudah menjadi kelaziman yang sekarang sulit untuk disangkal.
Mantan jurnalis Associated Press dan The Times of London yang kini menjadi profesor ilmu studi media di Toin University of Yokohama, Koichi Ishiyama mengatakan, bukan hanya politisi dan kementerian yang mampu membuat media di Jepang tunduk pada ancaman pengucilan
Tekanan Korporasi
Ishiyama menceritakan pengalamannya melakukan wawancara dengan perusahaan besar Jepang. Eksekutif mereka menerangkan dengan sangat jelas bahwa mereka tidak akan bekerja sama dengan permintaan informasi atau komentar apa pun dengan Ishiyama, karena dia telah menulis sesuatu tentang perusahaan yang menurut mereka negatif.
“Perusahaan bisa sama buruknya,” kata Ishiyama.
Perusahaan besar juga dapat memberikan jenis tekanan lain kepada media, kata Ishiyama, seperti yang ditunjukkan oleh skandal yang sudah berlangsung lama tetapi sebagian besar diabaikan seputar mogul, dunia hiburan Johnny Kitagawa.

Majalah berita mingguan Shukan Bunshun pertama kali melaporkan pada 1999 bahwa Kitagawa, pendiri agensi pencari bakat Johnny & Associates, melakukan pelecehan seksual terhadap calon bintang pop laki-laki.
Takut kehilangan ketenaran dan kekayaan, tidak ada pemuda yang mau mengajukan pengaduan resmi ke polisi. Akibatnya, Kitagawa tetap bebas untuk melecehkan lebih banyak anak laki-laki sampai saat kematiannya pada Juli 2019.
Meskipun aktivitas Kitagawa menjadi rahasia umum di dunia bisnis hiburan Jepang, media arus utama menutup-nutupi masalah tersebut. Perusahaan media mengatakan mereka tidak melihat adanya bukti kesalahan, dan kritikus mengatakan perusahaan ini tidak pernah mencari dengan cermat.
Wartawan dan Media Takut Masuk Daftar Hitam
“Media di sini membutuhkan bintang pop dan orang-orang ‘berbakat’ untuk tampil di program musik dan acara obrolan mereka, jadi mereka tidak pernah melaporkan tentang Kitagawa karena takut masuk daftar hitam,” kata Ishiyama.
Ishiyama menambahkan, dunia bisnis saling terhubung dengan sangat erat sehingga laporan tentang Kitagawa bisa berarti mereka kehilangan iklan, sponsor, dan akses ke bintang. Akibatnya, mereka lebih memilih sikap diam saja.
Seorang jurnalis Amerika yang telah bekerja untuk surat kabar Jepang selama 30 tahun mencatat, bahwa budaya penyensoran diri media Jepang sifatnya jauh lebih dalam lagi.
“Ini bukan jenis penyensoran resmi (seperti) yang kita lihat di Cina, Korea Utara, atau negara-negara lain yang berada di urutan paling bawah,” kata jurnalis yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena takut kehilangan pekerjaan.
Sang jurnalis itu menambahkan, itu bukan hanya penyensoran diri, yang berarti wartawan tidak mengajukan pertanyaan sulit. “Tidak ada suasana yang mendorong pembahasan isu-isu penting karena wartawan tahu bahwa jika mereka mengajukan pertanyaan sulit mereka dapat dihukum,” tandas dia.
Alhasil, media Jepang hanya melaporkan dengan tepat apa yang diinginkan oleh pemerintah dan korporasi besar berdasarkan pengarahan resmi.
“Dan itu, bagi saya, berarti media di sini sangat merugikan masyarakat,” tegas sang jurnalis. (DW/rs)